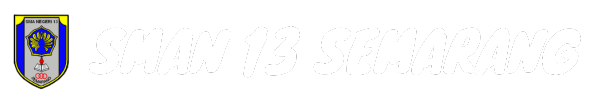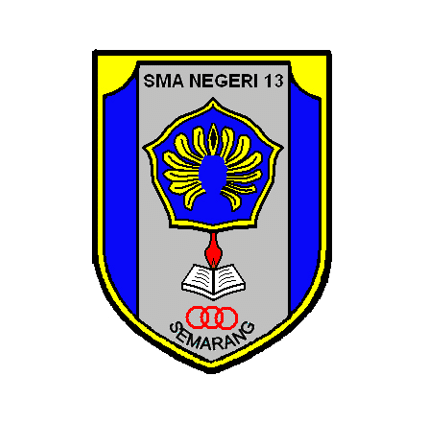- Selamat Datang di Website Resmi SMAN 13 Semarang
KEPRAMUKAAN SUDAH DEEP LEARNING, SEKOLAH MASIHKAH SURFACE LEARNING?

Oleh Widodo
Deep Learning sangat menarik karena menjanjikan pergeseran radikal dari Pembelajaran Permukaan (Surface Learning), yang hanya berfokus pada hafalan dan pemahaman dasar, menuju pemahaman konsep secara menyeluruh, kemampuan menghubungkan pengetahuan, dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan nyata.
Hal yang paling memesona dari Deep Learning adalah visinya “menumbuhkan generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan tangguh memecahkan masalah di tengah pusaran zaman yang tak menentu”. Gelombang pembaruan ini telah mengalir dari Australia hingga Finlandia, dari ruang-ruang kelas di Selandia Baru hingga laboratorium pendidikan Kanada. Di sanalah Deep Learning tumbuh sebagai praktik baik, dan Indonesia mulai menapaki jejak itu -mengirim instruktur, belajar dari Rob Randall, menyimak cara bangsa lain menenun makna belajar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga manusiawi.
Hari ini, kita sedang sibuk berbicara tentang deep learning, berpikir kritis, reflektif, kolaboratif, tetapi ruang kelas masih dipenuhi kursi berbaris, papan tulis yang kaku, dan evaluasi yang menilai seberapa banyak anak mengingat, bukan seberapa dalam mereka memahami. Sementara itu, di lapangan terbuka, di bawah langit dan di antara tenda-tenda lusuh, Pramuka diam-diam sudah melakukan deep learning sejak lama.
Pramuka mengajarkan anak untuk berpikir melalui tangan, bukan sekadar melalui kepala. Tali-temali bukan hafalan simpul, melainkan latihan logika, kesabaran, dan tanggung jawab. Api unggun bukan sekadar simbol romantis kegiatan malam, melainkan ruang kontemplasi tentang kebersamaan, keberanian, dan makna hidup. Berkemah bukan sekadar tidur di tenda dan memasak di alam terbuka, melainkan latihan kemandirian, gotong royong, dan pengelolaan diri dalam keterbatasan, tempat seseorang belajar menghadapi ketidaknyamanan dengan jiwa tangguh dan hati gembira. Sementara terjun ke lokasi bencana bukan sekadar aksi heroik menolong, melainkan ujian kemanusiaan, empati, dan ketulusan, di mana seseorang belajar bahwa membantu orang lain berarti siap berkorban tanpa pamrih, bekerja dalam situasi sulit, dan menegakkan nilai kemanusiaan di tengah penderitaan. Di situlah pembelajaran mendalam terjadi, bukan di atas kertas ulangan, tetapi di antara percakapan, kerja tim, dan refleksi atas kegagalan. Itu bukan surface learning, itu pembelajaran sejati: menyentuh kepala, hati, dan tangan sekaligus.

Ironi muncul ketika istilah deep learning menjadi jargon kebijakan, tapi kehilangan ruhnya di ruang kelas. Sebagian sekolah seolah berlari mengejar modernitas, kurikulum dengan pendekatan “baru”, perangkat digital, aplikasi canggih, tetapi lupa bahwa “dalam” bukan berarti “digital”. Deep learning bukan perkara teknologi, tapi perkara kesadaran. Bukan soal algoritma, tapi soal alasan kita belajar.
Bayangkan seorang murid yang mampu menjelaskan definisi AI dengan lancar, tapi tak bisa menyalakan api dapurnya tanpa bantuan orang lain. Ia cerdas, tapi tidak tangguh. Bandingkan dengan seorang Pramuka yang mungkin tak tahu teori machine learning, tapi mampu memimpin regunya menembus hutan, mengambil keputusan cepat, dan mengutamakan keselamatan bersama. Siapa yang lebih siap menghadapi hidup?
Pramuka sesungguhnya adalah wajah manusia dari deep learning. Di sana ada meaningful learning,karena setiap kegiatan punya makna sosial dan moral; ada mindful learning, karena setiap keputusan di lapangan menuntut kesadaran diri dan tanggung jawab; dan ada joyful learning, karena pembelajaran yang sejati memang menyenangkan, tidak terpaksa. Itulah tiga pilar pembelajaran mendalam yang oleh para ahli dikagumi di Australia, Finlandia, dan Kanada. Dan semua itu sudah lama hidup di bumi perkemahan, jauh sebelum istilahnya populer di seminar pendidikan.
Tapi ada paradoks besar: sekolah yang katanya modern justru makin dangkal, sedangkan Pramuka yang dianggap “tradisional” justru paling relevan dengan masa depan. Sekolah masih terobsesi pada skor, sedangkan Pramuka menumbuhkan karakter. Sekolah menakutkan anak dengan kesalahan, Pramuka membiarkan anak belajar dari jatuh bangun.
Jika dipikir-pikir, pendidikan kita seperti sedang membangun gedung tinggi di atas pasir. Kurikulum yang padat, administrasi yang menumpuk, guru yang kelelahan, semuanya menciptakan sistem surface learning yang memaksa anak berlari tanpa tahu arah. Kita membanjiri mereka dengan fakta, tapi menelantarkan rasa ingin tahu. Kita menjejalkan konsep, tapi tidak memberi ruang untuk merenung. Padahal, pembelajaran sejati tidak terjadi saat murid menulis jawaban di kertas ujian, tetapi saat mereka menulis ulang cara berpikirnya sendiri. Dan di sinilah kepramukaan kembali menjadi cermin yang menampar lembut wajah pendidikan kita.
Gerakan Pramuka adalah sekolah yang tak pernah mengaku sekolah, tetapi justru paling efektif mendidik. Ia melatih kepemimpinan tanpa modul manajemen. Ia membangun solidaritas tanpa butuh mata pelajaran “Profil Pelajar Pancasila”. Kepramukaan adalah deep learning in motion: pembelajaran yang hidup, bergerak, dan menyentuh kesadaran.
Namun, mari jujur juga: tidak semua kegiatan Pramuka sudah “dalam”. Banyak latihan yang kini kehilangan makna, sekadar seremonial. Banyak pembina yang nyaman dengan rutinitas, bukan refleksi. Di sinilah kritik harus diarahkan, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan. Pramuka punya akar pembelajaran mendalam, tapi jika tak disiram dengan inovasi dan refleksi, ia akan kering juga.
Maka, yang kita perlukan bukan lagi “mengajar Pramuka di sekolah”, tapi menjadikan Pramuka sebagai guru bagi sekolah. Guru perlu belajar sebagai pembina yang mengajarkan lewat tindakan, bukan hanya kata. Orangtua perlu belajar bahwa pendidikan terbaik bukan yang membuat anak ranking satu, tapi yang membuat anak sadar akan dirinya dan orang lain. Deep learning yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak anak tahu, tapi seberapa dalam mereka peduli.
Kini, saat AI mulai meniru pola pikir manusia, tantangan terbesar kita justru bukan melawan teknologi, tetapi menemukan kembali kedalaman manusia. AI bisa menulis puisi, tapi tidak bisa merasa sedih. AI bisa membuat rencana kegiatan, tapi tidak bisa mencium aroma tanah setelah hujan di perkemahan. AI bisa meniru logika, tapi tidak bisa menggantikan kesadaran.
Dan di sinilah kepramukaan memegang peran kunci: membangun manusia yang sadar, bukan sekadar pintar. Mendidik anak untuk berpikir reflektif, bukan hanya responsif. Membiasakan mereka untuk mengalami, bukan sekadar menghafal. Karena, seperti kata pepatah lama: air yang tenang itu dalam, tapi tidak semua yang dalam harus tenang, kadang kedalaman itu justru lahir dari keberanian untuk mengaduk permukaan.
“Orang yang benar-benar belajar tidak hanya tahu jawabannya, tapi juga paham alasannya.”
*penulis: Widodo, Wakil Kepala Pusdiklat Kwarcab Kota Semarang,
Pembina Pramuka SMAN 13 Semarang